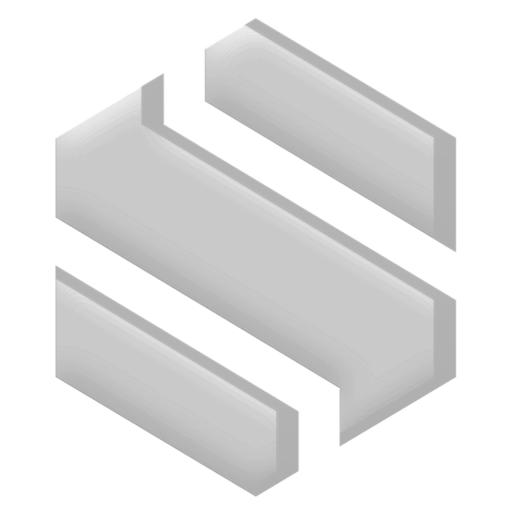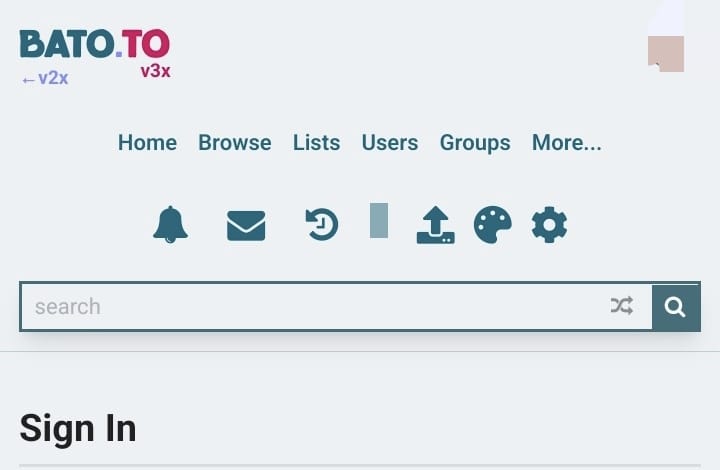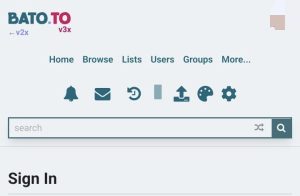Nasional, Sketsa.id – Isu royalti musik kembali memantik diskusi di ruang publik. Sejak kasus Ari Bias melawan Agnez Mo mencuat awal tahun ini dan berujung denda miliaran rupiah, polemik soal siapa yang sebenarnya berhak menerima royalti dan siapa yang wajib membayarnya makin meruncing. Tak hanya menyentuh ranah industri musik, imbasnya terasa hingga ke sudut-sudut kafe dan restoran di berbagai kota. Tak sedikit pelaku usaha mengaku tertekan dan memilih berhenti memutar lagu, khawatir harus membayar kewajiban yang mereka anggap belum sepenuhnya jelas.
Di tengah gonjang-ganjing itu, suara dari musisi senior pun muncul. Gitaris grup band Padi Reborn, Piyu, buka suara soal fenomena para pemilik kafe yang takut memutar musik. Menurutnya, keresahan ini seharusnya tidak perlu ada jika semua pihak memahami dasar hukumnya. “Gak usah takut (putar lagu di ruang publik), karena itu sebenarnya sudah diatur dari tahun 2014,” ujar Piyu saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025). Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara tegas mengatur hak ekonomi pencipta, termasuk ketika karya mereka digunakan di ruang-ruang komersial.
Piyu sendiri adalah bagian dari kelompok musisi yang tergabung dalam AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia), yang selama ini mendukung penegakan hak cipta secara adil. Namun dalam keterangannya, ia tidak menempatkan musisi sebagai pihak yang menekan, melainkan mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara rasional dan berbasis aturan hukum yang sudah berlaku hampir satu dekade. “Sekarang tunggu saja hasilnya, nanti kita akan katakan,” tambahnya.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menjelaskan bahwa penggunaan musik di ruang usaha seperti restoran, hotel, kafe, hingga gym memang wajib membayar royalti, meskipun pemilik usaha menggunakan platform streaming berbayar seperti Spotify Premium atau YouTube Music. Langganan tersebut tidak mencakup penggunaan untuk ruang publik. Royalti yang dikumpulkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akan disalurkan kepada para pencipta lagu sesuai frekuensi dan tempat karya mereka digunakan.
Namun polemik tak berhenti di sana. Para pelaku usaha merasa terbebani dengan sistem yang menurut mereka belum transparan dan belum sepenuhnya dipahami. Beberapa bahkan sempat mewacanakan pemboikotan lagu-lagu Indonesia di ruang usaha mereka. Merespons hal itu, DJKI menyarankan alternatif: gunakan musik bebas royalti, karya ciptaan sendiri, hingga suara ambience seperti air terjun atau alam terbuka. DJKI juga menegaskan bahwa tarif royalti disesuaikan dengan kapasitas dan jenis usaha—untuk kafe kecil, misalnya, dikenakan tarif sekitar Rp 720 per meter persegi per bulan, atau Rp 120.000 per kursi per tahun.
Untuk menjawab tuntutan transparansi, LMKN kini telah meluncurkan platform digital bernama Velodiva. Dengan teknologi AI, Velodiva bisa mendeteksi lagu yang diputar di ruang publik, mencatat waktu, dan menghubungkannya langsung dengan database hak cipta. Sistem ini diharapkan bisa menjamin bahwa setiap pencipta mendapatkan haknya secara adil, tanpa tumpang tindih atau kesalahan distribusi.
Polemik ini juga memecah dua kutub di kalangan musisi. Di satu sisi, kelompok seperti VISI (Voice of Indonesia) yang terdiri dari nama-nama besar seperti Ariel, Armand Maulana, dan Rossa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar pengelolaan royalti lebih fleksibel dan tidak membebani pelaku seni pertunjukan. Di sisi lain, pencipta lagu yang tergabung dalam AKSI tetap mendukung mekanisme LMKN, namun membuka opsi lisensi langsung melalui sistem digital tanpa lembaga perantara.
Meski tampak kompleks, satu hal yang tak bisa diabaikan adalah bahwa industri musik sedang mencari jalan baru. Data industri menunjukkan pertumbuhan positif—royalti streaming meningkat 14 persen sepanjang 2024, dan 60–70 persen tangga lagu lokal kini diisi musisi dalam negeri. Pencipta lagu, penyanyi, pelaku usaha, dan pemerintah kini tengah berada di meja yang sama, meski masih dalam posisi yang berbeda.
Bagi Piyu, semuanya kembali pada kesadaran bersama. Hak cipta bukan sekadar urusan hukum, tapi bentuk penghargaan terhadap karya dan proses kreatif.
“Kita harus saling ngerti. Jangan saling salah paham,” ucapnya sebelum meninggalkan lokasi. Satu kalimat singkat, tapi menggambarkan harapan banyak orang: bahwa musik tak seharusnya jadi sumber ketakutan, tapi tetap bisa dinikmati semua orang dengan cara yang adil. (*)