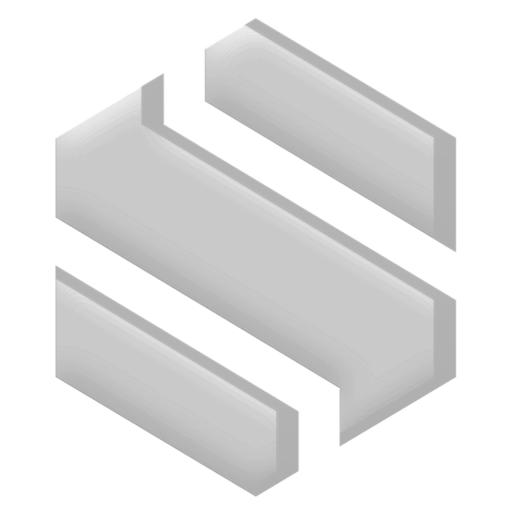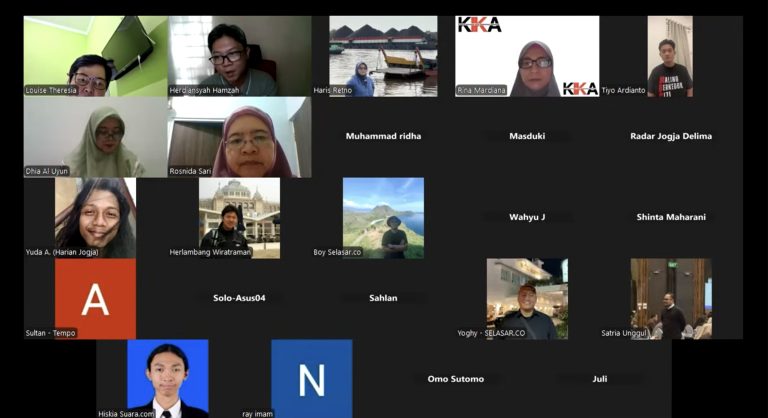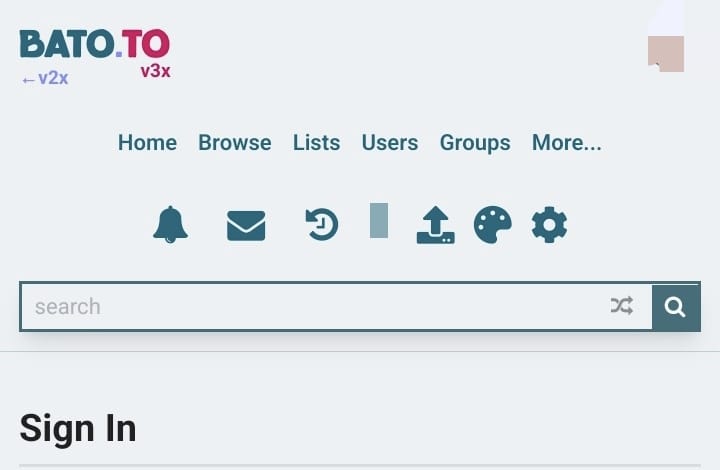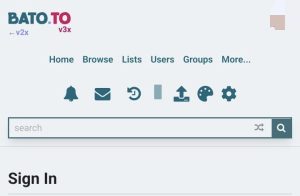Nasional, Sketsa.id – Di tengah sorotan publik, Sri Mulyani mencoba menjelaskan paradoks anggaran pendidikan dengan dua argumen utama. Pertama, jumlah guru Indonesia yang mencapai 4,3 juta – terbesar kedua di dunia – membuat alokasi per kapita menjadi kecil. Kedua, rasio gaji guru terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 4,2%, lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 3,8%. Namun, penjelasan ini justru menuai kritik lebih tajam dari kalangan pakar pendidikan.
Prof. Ahmad Baedowi dari Universitas Indonesia menyoroti masalah distribusi yang timpang.
“Anggaran besar itu menguap di tengah jalan, tak pernah sampai ke guru-guru di garis depan,” ujarnya.
Kritik serupa datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang menilai sistem sertifikasi guru selama ini gagal meningkatkan kesejahteraan riil.
“Tunjangan profesi tak ada artinya ketika harga kebutuhan pokok melambung tinggi,” tegas seorang perwakilan FSGI.
Di lapangan, janji evaluasi pemerintah belum membuahkan terobosan berarti. Tunjangan guru tak kunjung disesuaikan dengan laju inflasi yang mencapai 6,5% di awal 2025. Program pelatihan guru pun hanya menjangkau 28% pendidik, sementara rasio guru-murid masih jauh dari standar UNESCO. Di banyak sekolah, seorang guru harus menangani 50 murid sekaligus, padahal standar internasional menganjurkan maksimal 20 murid per guru.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sampai kapan guru Indonesia harus terjebak dalam lingkaran setan antara anggaran besar dan kesejahteraan minim? Padahal, solusi sebenarnya sudah sering diungkapkan berbagai pihak – mulai dari perbaikan sistem distribusi anggaran, penyesuaian gaji sesuai beban kerja, hingga reformasi menyeluruh sistem sertifikasi guru.
Namun, semua masih terasa seperti janji yang menggantung, sementara jutaan guru terus bergulat dengan realita penghidupan yang semakin sulit.(*)