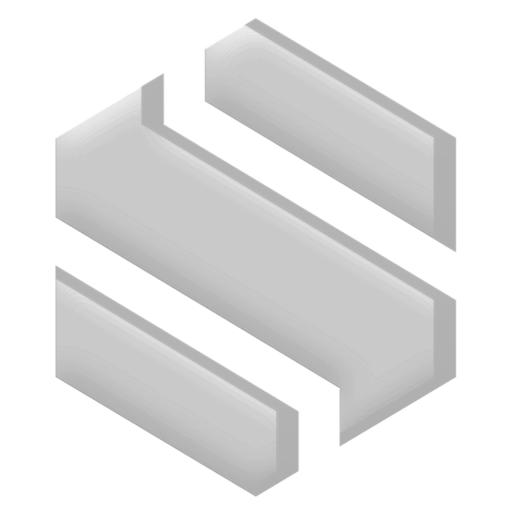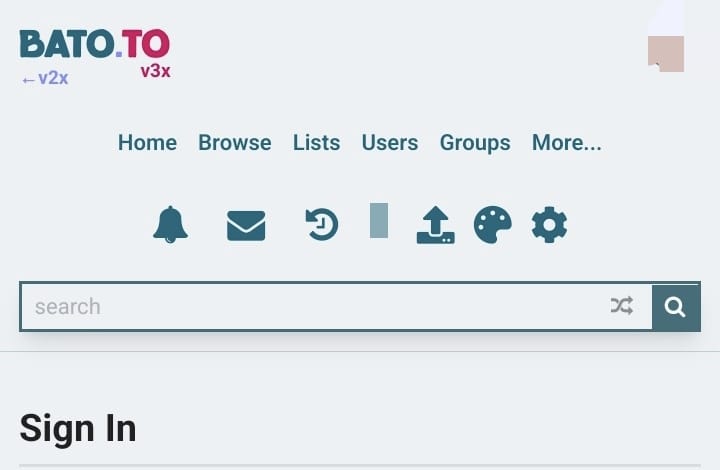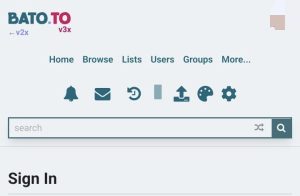Aceh, Sketsa.id – Kabupaten Aceh Tamiang, yang sering disebut-sebut sebagai daerah rawan banjir karena posisinya di hilir Sungai Tamiang, kembali menjadi korban utama bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Banjir bandang yang dipicu hujan deras ekstrem sejak 26 November itu tidak main-main: desa-desa lenyap tertimbun lumpur dan gelondongan kayu, ratusan ribu warga mengungsi, dan puluhan nyawa melayang. Data dari berbagai sumber kredibel seperti BNPB, BPBD Aceh Tamiang, dan laporan media nasional menunjukkan skala kerusakan yang mengerikan.
Menurut rekap BPBD Aceh Tamiang hingga awal Desember, setidaknya 57-60 orang meninggal dunia, 22 hilang, dan lebih dari 262.000 jiwa mengungsi—angka yang kemudian menurun menjadi sekitar 208.000 pengungsi saat air mulai surut. Ribuan rumah rusak berat atau hanyut, termasuk 780 unit yang benar-benar lenyap. Desa seperti Sekumur di Kecamatan Karang Baru hanya menyisakan masjid di tengah lautan kayu dan lumpur. Pondok pesantren dan sekolah berasrama pun tak luput, tertutup endapan tebal yang membuat akses nyaris mustahil.
Warga bertahan dengan cara yang memilukan: berenang dari atap ke atap mencari makanan, memungut roti hanyut, atau bahkan menyeduh susu bayi dengan air banjir yang keruh. Krisis air bersih menjadi momok utama—banyak yang belum mandi berhari-hari, memicu penyakit seperti demam, batuk, dan gatal-gatal. Listrik padam total, sinyal hilang, membuat daerah ini seperti “kota zombie” yang gelap gulita, seperti yang digambarkan warga dan media.
Yang lebih menyakitkan hati adalah lambannya respons awal. Beberapa wilayah terisolasi berhari-hari, bantuan baru masuk signifikan sekitar 1 Desember. Warga terpaksa evakuasi sendiri, bahkan ada yang menerobos hutan untuk keluar ke Medan. Presiden Prabowo Subianto baru meninjau pada 12 Desember, disusul menteri-menteri. Sementara itu, Pemerintah Aceh akhirnya resmi meminta bantuan dua lembaga PBB—UNDP dan UNICEF—pada pertengahan Desember, mengakui pengalaman tsunami 2004 bisa jadi pelajaran berharga untuk pemulihan. Langkah ini, meski terlambat, setidaknya mengakui bahwa penanganan domestik saja tak cukup cepat.
Tak ketinggalan, ada pernyataan pejabat yang bikin geleng-geleng kepala. Bupati Aceh Tamiang menyebut julukan “kota zombie” hanya isu yang “memperkeruh suasana“, seolah kondisi gelap dan sunyi itu cuma hoaks. Di level nasional, ada yang bilang situasi mencekam “hanya berseliweran di media sosial“—padahal foto dan video itu datang langsung dari warga yang putus asa teriak minta tolong.
Bencana ini bukan sekadar “musibah alam“. Pakar dari BRIN dan aktivis lingkungan menyoroti degradasi hutan, pembalakan liar, dan konversi lahan yang memperparah banjir bandang. Aceh Tamiang bukan kali pertama dilanda tragedy serupa—ingat banjir 2006?—tapi pelajaran seolah tak pernah diambil serius.
Kini, saat air surut, tantangan baru muncul: relokasi warga karena banyak lokasi tak layak huni lagi, risiko penyakit pasca-banjir, dan pemulihan ekonomi. Relawan dari berbagai NGO, termasuk internasional, mulai berdatangan, membawa harapan di tengah keterlambatan birokrasi.
Tragedi Aceh Tamiang 2025 ini mengingatkan kita: bencana tak kenal ampun, tapi respons yang cepat dan empati bisa menyelamatkan nyawa. Semoga ini jadi cambuk untuk mitigasi lebih baik, bukan sekadar janji manis saat kamera menyala. Warga Aceh Tamiang pantas bangkit lebih kuat—dengan atau tanpa “tongkat sulap” dari siapa pun. (*)