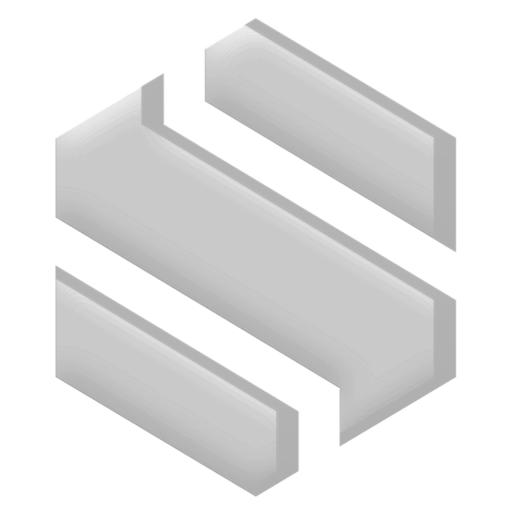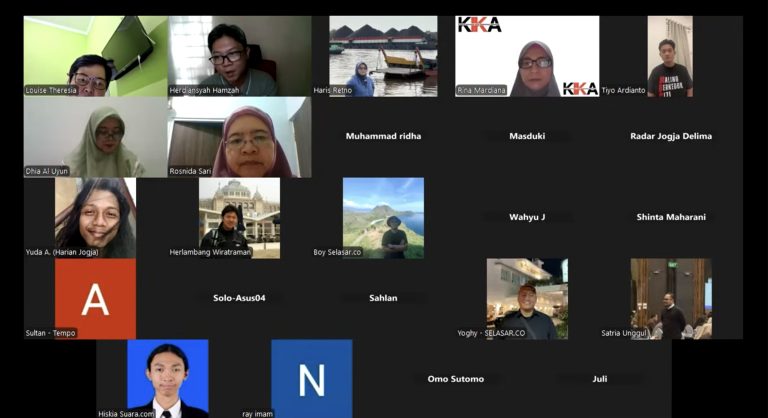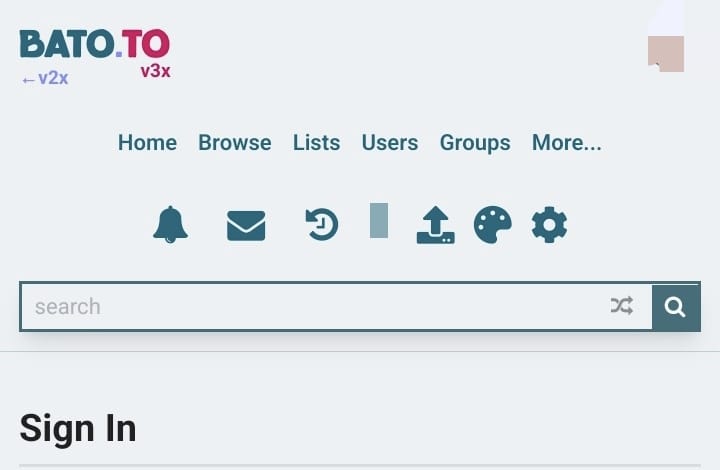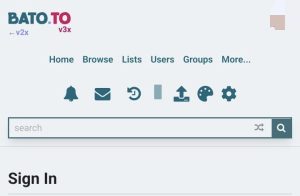Sketsa.id – Tanggal 22 Desember selalu menyisakan ruang untuk dua narasi yang kerap bersinggungan. Di satu sisi, ada refleksi mendalam tentang pengorbanan, kelahiran, dan kasih tanpa syarat. Di sisi lain, ada hiruk-pikuk komersial, unggahan media sosial yang terkurasi rapi, dan ekspresi terima kasih yang terkadang terasa seperti rutinitas. Namun, justru di ketegangan antara yang filosofis dan yang praktis, yang sakral dan yang duniawi inilah, Hari Ibu menemukan relevansinya yang terus berkembang.
Akar Konseptual: Ibu Sebagai Metafora Keberadaan
Jauh sebelum menjadi momen di kalender, konsep “Ibu” telah mengakar dalam tradisi pemikiran manusia sebagai sebuah prinsip penciptaan. Filsuf Yunani seperti Aristoteles melihat ibu sebagai “materi pertama” (hylē prōtē) yang memberikan bentuk pada potensi kehidupan. Dalam tradisi Hindu, ada Shakti, energi feminin primordial yang menjadi sumber segala penciptaan. Sementara dalam mistisisme berbagai agama, gambaran Tuhan yang “menyusui” atau merawat jiwa manusia sering digunakan, menunjukkan bagaimana bahasa keibuan dipakai untuk menggambarkan kasih sayang yang paling intim dan transenden.
Narasi-narasi kuno ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merayakan seorang ibu, kita tak hanya menghormati individu, tetapi juga menyentuh salah satu arketipe tertua dalam peradaban: sosok pemberi kehidupan dan pemelihara.
Secara resmi di Indonesia, Hari Ibu berawal dari semangat emansipasi dan perjuangan kolektif. Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 1928 menjadi tonggak yang membahas isu-isu substantif seperti pendidikan, hak politik, dan perlawanan terhadap perkawinan anak.
Seiring waktu, fokus peringatan ini mengalami pergeseran. Dari semangat pergerakan, ia bergerak menuju ruang domestik keluarga, kemudian terdorong oleh gelombang konsumerisme, dan kini menemukan ekspresi barunya di panggung media sosial. Ungkapan syukur yang dulu mungkin terucap secara privat, kini sering terkemas dalam visual yang indah dan kata-kata yang terstandarisasi di linimasa.
Relevansi di 2025: Mengakui Kerumitan, Melampaui Kesempurnaan
Di tengah tuntutan zaman yang semakin kompleks, beban pada sosok ibu justru bertambah. Ibu masa kini sering diharapkan untuk menjadi multitasker sempurna: berkarier, menjadi pengasuh utama, menjaga penampilan, dan sekaligus menjaga kesehatan mental di tengah banjir informasi tentang pola asuh yang “ideal“. Tekanan untuk tampil sempurna ini dapat memunculkan rasa bersalah yang konstan.
Oleh karena itu, mungkin makna Hari Ibu yang paling penting di era sekarang justru bukan terletak pada pemberian hadiah, tetapi pada pemberian pengakuan dan ruang. Ruang bagi seorang ibu untuk merasa lelah tanpa merasa gagal. Pengakuan bahwa mengasuh manusia lain adalah pekerjaan yang luar biasa berat dan mulia, dan nilainya tidak perlu dibuktikan dengan kesempurnaan penampilan di ranah digital.
Jika boleh meminjam kalimat dari seorang filsuf kontemporer yang agak sinis tapi jujur, Byung-Chul Han:
“Kasih sayang yang sejati adalah kasih yang tidak menuntut produktivitas emosional dari yang dikasihi.”
Selamat Hari Ibu.
Bukan karena kamu sempurna, tapi justru karena kamu manusia yang tetap memilih untuk terus mengasihi meski seringkali dengan tangan yang gemetar. (*)