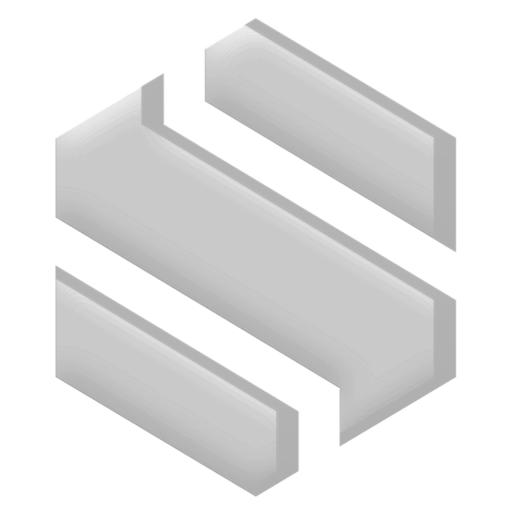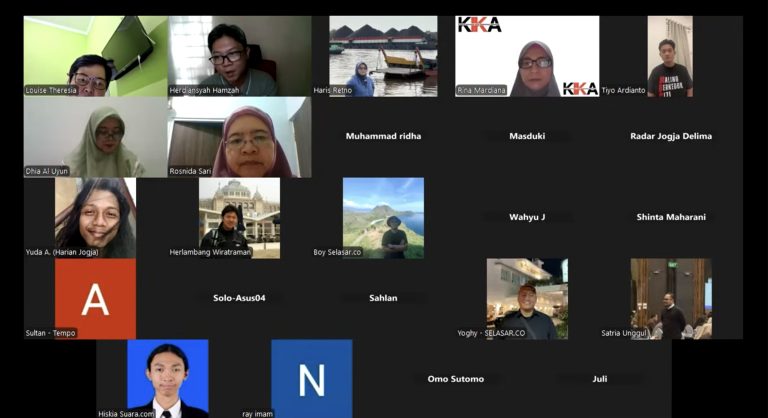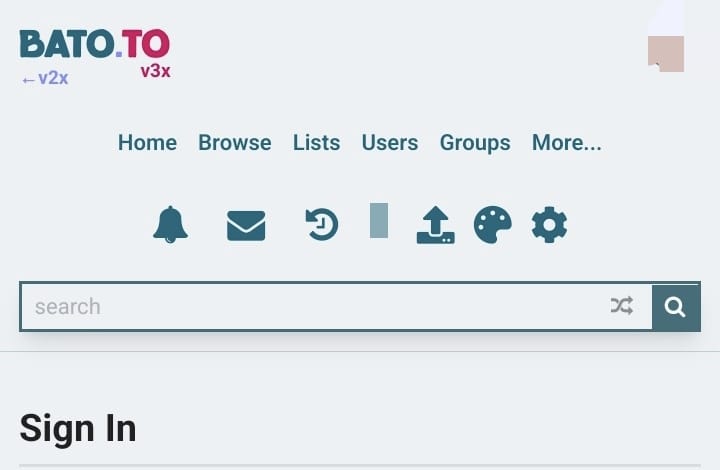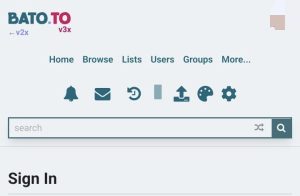Sketsa.id – Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia. Lebih dari sekadar kisah pembunuhan enam jenderal, peristiwa ini menjadi pemicu genosida massal, pergolakan politik, dan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bagi generasi muda, G30S bukan hanya pelajaran sejarah, tetapi cermin bagaimana ambisi kekuasaan, propaganda, dan campur tangan asing dapat menghancurkan bangsa. Artikel ini menggali fakta-fakta yang jarang dibahas di kelas sejarah, namun krusial untuk dipahami agar generasi sekarang tidak terjebak dalam polarisasi dan hoaks serupa.
Latar Belakang: Indonesia di Ujung Perang Dingin
Pada 1965, Indonesia berada dalam ketegangan politik ekstrem. Presiden Soekarno mendorong konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme) untuk menyatukan faksi-faksi yang saling bertentangan. Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan jutaan anggota dan pendukung, menjadi kekuatan politik besar, mendukung kebijakan anti-imperialisme Soekarno seperti Konfrontasi dengan Malaysia. Namun, pengaruh PKI memicu friksi dengan Angkatan Darat (AD), yang sebagian besar anti-komunis.
Ekonomi Indonesia kala itu terpuruk: inflasi mencapai ratusan persen, korupsi merajalela, dan konflik agraria antara petani PKI dan tuan tanah memanas. Di panggung global, Perang Dingin memperkeruh situasi. Amerika Serikat (AS) dan Inggris khawatir Indonesia condong ke blok komunis, terutama karena kedekatan Soekarno dengan Tiongkok. Dokumen rahasia Kedutaan AS di Jakarta (1963–1966) mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap PKI sebagai “ancaman strategis.” Sementara itu, militer Indonesia terpecah antara faksi pro-Soekarno dan faksi pro-Barat yang didukung pelatihan serta peralatan dari AS.
Isu “Dewan Jenderal” yang konon akan mengkudeta Soekarno menjadi pemicu G30S. Kelompok perwira muda yang loyal kepada presiden merasa terancam, mendorong mereka untuk bertindak.
Kronologi: Malam Kelam 30 September
Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa di bawah komando Letkol Untung Syamsuri melancarkan operasi. Mereka menyerbu rumah enam jenderal senior AD: Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Mayjen D.I. Pandjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Selain itu, Letnan Satu Pierre Tendean (ajudan Jenderal Nasution yang disangka sebagai Nasution) dan beberapa polisi tewas. Jenderal A.H. Nasution lolos, namun putrinya, Ade Irma, tewas tertembak.
Jasad para korban dibuang ke sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur—kini dikenal sebagai Monumen Pancasila Sakti. Pagi harinya, Untung mengumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) bahwa G30S telah “mengamankan Soekarno” dari rencana kudeta. Namun, gerakan ini lemah: hanya melibatkan kurang dari 100 orang dan tidak memiliki strategi lanjutan.
Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, dengan cepat mengambil alih komando. Pada 1 Oktober sore, pasukan Kostrad merebut kembali RRI dan Lanud Halim, markas G30S. Dalam hitungan hari, Untung dan pemimpin lainnya ditangkap. Militer menuding PKI sebagai dalang, meski bukti keterlibatan langsung PKI masih diperdebatkan hingga kini.
Dampak: Dari Kudeta Gagal ke Genosida
G30S menjadi katalis tragedi besar. Tuduhan terhadap PKI memicu pembantaian massal dari Oktober 1965 hingga Maret 1966. Militer, dibantu kelompok sipil seperti Ansor NU dan pemuda anti-komunis, membunuh ratusan ribu hingga jutaan orang—anggota PKI, simpatisan, bahkan warga biasa yang dituduh tanpa bukti. Kekerasan paling parah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dengan mayat-mayat mengapung di sungai, kamp konsentrasi dadakan, dan kekerasan seksual terhadap anggota Gerwani.
Estimasi korban bervariasi antara 500.000 hingga 3 juta jiwa, menjadikannya salah satu pembantaian terbesar abad ke-20. PKI dibubarkan, komunisme dilarang, dan Soekarno dilengserkan secara bertahap melalui Supersemar pada 11 Maret 1966. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, mendirikan Orde Baru yang berkuasa hingga 1998.
Fakta Tersembunyi: Apa yang Tak Diajarkan di Sekolah, Tapi Generasi Muda Wajib Tahu
Pelajaran sejarah sekolah sering menyederhanakan G30S sebagai “pengkhianatan PKI,” diperkuat oleh propaganda Orde Baru seperti film Pengkhianatan G30S/PKI. Namun, dokumen dan penelitian mutakhir mengungkap lapisan yang lebih kompleks—fakta yang tidak diajarkan, tetapi penting untuk dipahami agar generasi muda kritis terhadap narasi resmi.
- Campur Tangan AS dalam Pembantaian: Dokumen deklasifikasi Kedutaan AS di Jakarta, dirilis oleh National Security Archive pada 2017, menunjukkan AS mengetahui dan mendukung pembantaian massal. Mereka memantau eksekusi PKI per provinsi, memberikan daftar nama anggota PKI kepada militer Indonesia, serta menyediakan peralatan komunikasi dan dana. Diplomat AS Marshall Green disebut “mendorong” pembersihan untuk mencegah Indonesia menjadi “domino komunis.” Ini menunjukkan peran asing yang signifikan, yang jarang dibahas di sekolah.
- Propaganda Inggris untuk Memanaskan Konflik: Dokumen Foreign Office Inggris (2021) mengungkapkan bahwa Information Research Department (IRD) menyebarkan propaganda anti-komunis melalui radio gelap. Mereka mendesak militer untuk “memotong kanker komunis” dan memalsukan cerita kekejaman PKI untuk memicu histeria. Ini adalah bagian dari strategi Perang Dingin untuk melemahkan Soekarno dan PKI, yang memperparah kekerasan.
- Soeharto Mengatur Kekuasaan Sejak Awal: Penelitian Jess Melvin dalam The Army and the Indonesian Genocide (2018) menunjukkan bahwa Soeharto memanfaatkan G30S sebagai alasan untuk kudeta merangkak. Militer telah menyiapkan daftar target pembersihan sebelum G30S, menunjukkan bahwa pembantaian bukan reaksi spontan, melainkan strategi terencana untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Soeharto, bukan sekadar “penyelamat,” memainkan peran kunci dalam mengarahkan narasi anti-PKI.
- Korban Tak Bersalah dan Trauma Abadi: Banyak korban bukan komunis, melainkan petani, buruh, seniman, atau etnis Tionghoa yang dituduh tanpa bukti. Geoffrey Robinson dalam The Killing Season (2018) mencatat hingga 80.000 orang tewas di Bali saja dalam “musim pembunuhan.” Trauma ini berlanjut: keturunan korban menghadapi diskriminasi, dan diskusi tentang 1965 tetap sensitif hingga kini. John Roosa dalam Pretext for Mass Murder (2006) menyebutnya sebagai “pembersihan sistematis” yang diabadikan untuk legitimasi Orde Baru.
Refleksi: Menyuarakan Kebenaran untuk Masa Depan
G30S/PKI adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya hitam-putih. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana kekuasaan, propaganda, dan konflik global dapat menghancurkan jutaan nyawa. Generasi muda harus belajar dari fakta-fakta ini, bukan untuk membenci, tetapi untuk menjaga demokrasi dan kemanusiaan. Di era media sosial, kemampuan membedakan kebenaran dari hoaks adalah senjata terpenting.
Seperti dikatakan Jess Melvin, “Sejarah ini bukan milik penguasa, tetapi milik kita semua.”
Mari jadikan 30 September sebagai hari refleksi untuk membangun masa depan yang lebih adil dan terbuka. (*)