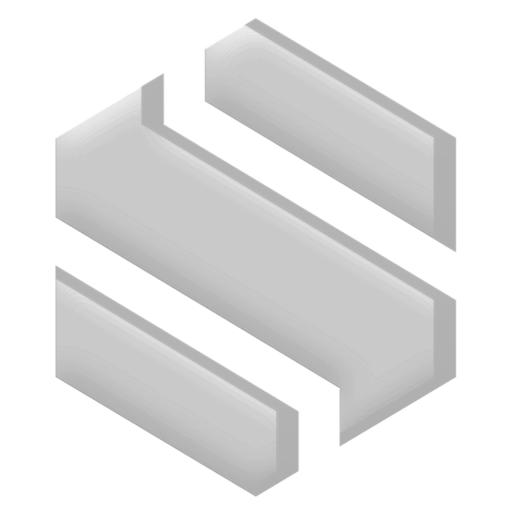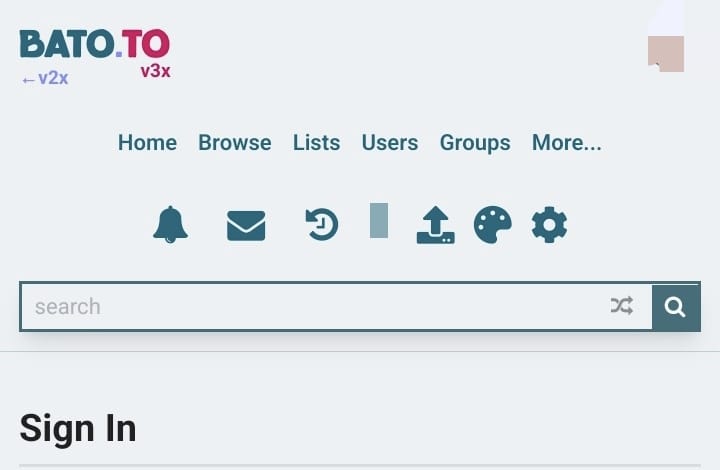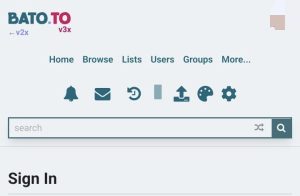Samarinda, Sketsa.id – Kasus bom Molotov yang menyelimuti aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kaltim pada 1 September lalu tidak hanya meninggalkan jejak asap, tetapi juga awan tebal pertanyaan tentang proporsionalitas penegakan hukum dan kebebasan menyampaikan kritik. Polresta Samarinda, setelah menangguhkan penahanan empat mahasiswa tersangka, akhirnya meringkus dua orang yang diduga sebagai otak intelektualnya: N (38), mantan mahasiswa, dan AJM (43), warga dari Sumatera.
Namun, di balik narasi penegakan hukum yang berjalan cepat ini, muncul suara-suara kritis yang mempertanyakan motif dan arah dari seluruh proses hukum tersebut. Herdiansyah Hamzah, atau yang akrab disapa Castro, seorang akademisi Universitas Mulawarman, memberikan pisau analisa yang tajam. Ia melihat kasus ini bukan sebagai insiden yang berdiri sendiri, melainkan sebuah reaksi dan bagian dari pola yang lebih besar.
Kekecewaan yang Meledak menjadi Molotov

Castro menegaskan bahwa masyarakat sepatutnya tidak bersepakat dengan aksi vandalisme, termasuk bom Molotov. Namun, yang luput dari pemberitaan dominan adalah akar persoalannya.
“Tapi juga harus dipahami, itu kan adalah reaksi yang muncul akibat kekecewaan, akumulasi kekecewaan terhadap negara, pemerintah dan DPR terutama. Sehingga aksi-aksi semacam ini muncul, kan itu yang harus dipahami,” papar Castro.
Menurutnya, yang justru semakin dominan dalam pemberitaan dan narasi pemerintah adalah soal “Molotovnya”, sementara esensi dari unjuk rasa itu sendiri—yaitu kritik terhadap kebijakan pemerintah dan DPR—justru tenggelam.
“Padahal isu utamanya adalah kritik publik terhadap pemerintah dan DPR, isu terhadap kebijakan-kebijakan. Nah sekarang soal-olah itu ditarik-tarik, dinegasikan ke persoalan Molotovnya gitu,” tambahnya.
Castro menangkap adanya pola black campaign operasi mencari kambing hitam yang bertujuan untuk meredam suara kritis. Ia mengaitkannya dengan peristiwa lain, seperti laporan terhadap Ferry Irwandi ke Mabes TNI yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum yang memadai.
“Kasusnya DPR misalnya, kasusnya sebanyak yang ditangkap. Kemarin sempat diwacanakan, Ferry Irwandi dilaporkan oleh Mabes TNI padahal tidak punya dasar hukum yang memadai. Soal-olah di cari-carikan alasan. Itu kita lihat sebagai operasi kambing hitam,” tegasnya.
Pola ini, menurutnya, adalah strategi untuk memindahkan basis persoalan. “Jadi rencana ini seperti ingin memindahkan basis persoalan dari kritik terhadap pemerintah, terhadap DPR ke persoalan hukum. Jadi ini kan sekarang pemberitaan didominasi dengan pemberitaan mengenai hukum, sementara kritik publik terhadap pemerintah, DPR dengan sebuah kebijakan itu menjadi tenggelam. Itu yang saya tangkap sebagai motif utamanya.”
Restorative Justice atau Sekadar Pemanis?
Sebelumnya, Castro juga menyoroti penangguhan penahanan terhadap empat mahasiswa dengan kerangka *restorative justice*. Meski melihat celah untuk penyelesaian yang memanusiakan, analisis utamanya justru menyoroti keanehan dan kecepatan proses hukum kasus Molotov ini dibandingkan dengan kasus-kasus besar seperti tambang ilegal yang berjalan lambat, bahkan mandek.
“Aneh proses hukum molotov ini. 1000 kali lebih cepat dibanding kasus-kasus tambang ilegal. Kacau!” serunya.
Pernyataan ini memperkuat thesisnya bahwa ada ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Kasus yang melibatkan kritik terhadap penguasa ditangani secara cepat dan keras, sementara kasus yang melibatkan pemodal besar dan perusakan lingkungan seringkali diselesaikan dengan lamban.
Dengan demikian, kasus bom Molotov di Samarinda telah berubah menjadi cermin yang memantulkan dua wajah: pertama, wajah penegakan hukum yang tampak progresif dengan konsep restorative justice; dan kedua, wajah represif yang berpotensi mengkriminalisasi gerakan kritik dan mengalihkan perhatian publik dari substansi kebijakan yang seharusnya dikoreksi. (*)